“KEBUDAYAAN adalah keseluruhan gagasan, tindakan dan taktik manusia dalam merespon alam, lingkungan dan sesamanya. Semua yang dilakukan, diciptakan dan dilatihkan dapat disebut kebudayaan. Norma, moral dan agama juga bagian dari kebudayaan, “ tutur Antariksa, salah satu tokoh muda yang juga pengurus KUNCI.
Menurutnya, kebudayaan dibebani oleh nilai-nilai serta berkaitan dengan ketergantungan pada nilai yang lain. Ia juga selalu berubah. Contohnya di era Soekarno. Kebudayaan dibuat sangat politis sedang era Suharto dibuat sedemikian tidak politis, sebab jika kebudayaan itu tidak senada dengan kepentingan penguasa ia dianggap membahayakan.
Apakah kebudayaan dibentuk oleh nalar politik seseorang dan sengaja diarahkan pada satu ideologi tertentu atau sebaliknya ? Hubungan keduanya bertimbal balik. Bisa jadi nalar mengubah kebudayaan tetapi bisa juga keadaan yang kita alami sehari-hari membentuk nalar kita. Jadi kebudayaan selalu politis dan menjadi arena pertarungan kepentingan.
Budaya Kekerasan
Ada anggapan, budaya kekerasan di Indonesia bermula dari Tragedi ’65. Tapi menurut Antariksa, hal itu tidak sepenuhnya benar. “Jauh sebelumnya bangsa kita punya sejarah kekerasan yang panjang. Hanya saja, Tragedi ‘65 merupakan tonggak penting karena budaya kekerasan itu dilembagakan dalam skala yang sangat besar dan didukung oleh alat-alat kekerasan yakni tentara dan produk hukum,” tuturnya
Ia juga menambahkan, kelembagaan yang diciptakan Orde Baru menciptakan satu pikiran bahwa, misalnya komunis itu jahat, komunis itu brengsek, komunis itu berbahaya. Yang lebih ngeri lagi, kekerasan dilembagakan dalam bentuk laten sifatnya, misalnya lewat kurikulum, ceramah, tuturan orang tua, film dan lain sebagainya. “Inilah yang tidak pernah terjadi sebelum ’65,” ungkap Antariksa.
Krisis kebudayaan dialami oleh setiap orang di seluruh dunia termasuk Indonesia. Salah satu krisis paling berbahaya – dan herannya kita tidak menganggapnya sebagai hal yang keliru – adalah homogenisasi (penyeragaman) kebudayaan.
“Kalau kita ke Aceh atau Papua, kita akan menemukan semuanya sama. Bajunya sama, cara bicaranya sama, bahkan cara berpikirnya juga dibuat sama. Semua diseragamkan oleh kepentingan uang. Disini tampak bahwa negara makin kehilangan perannya dalam politik kebudayaan. Peran tersebut telah digantikan oleh kekuatan modal ekonomi dan diutamakan atas nama modernisasi sebagai ukuran kemajuan suatu bangsa,” ujar Antariksa.
Salah Satu Alat
Menurutnya, negara seharusnya mengambil peran dalam kebijakan kebudayaan dan melindungi kebudayaan rakyat. Sebagai contoh, masuknya budaya asing melalui media elektronik.
“Menurut saya lembaga sensor adalah solusi paling tolol dan paling malas karena dibalik kebijakan sensor ada anggapan bahwa masyarakat itu bodoh dan harus diatur-atur. Didunia ini banyak kejahatan dan keburukan. Kenapa tidak membuat pendidikan media literasi dan penguatan-penguatan di bidang pendidikan? Itu lebih masuk akal,” ujarnya.
“Menentukan tolak ukur maju tidaknya sebuah kebudayaan itu sulit karena kita hanya bisa bicara dalam skala yang massif yakni negara. Yang bisa diukur adalah bagaimana lembaga-lembaga negara memperlakukan kebudayaan, bagaimana budaya itu hidup, apakah kebijakan kebudayaan bisa memerdekakan masyarakat, apakah kebudayaan yang dijalankan pro kepentingan rakyat, dll. Dari material inilah kita baru bisa mengukurnya,” tuturnya.
Terkait dengan peranan budaya sebagai pembangun karakter bangsa, kebudayaan bukanlah koridor atau alat utama. Kebudayaan hanyalah salah satu alat saja dan harus dijalankan berbarengan dengan koridor-koridor yang lain, misalnya koridor politik, ekonomi, dsb. Jadi semuanya saling melengkapi. (Sari Anantya Rosa)
Sumber: http://www.syarikat.org/article/
Rabu, 21 Januari 2009
Langganan:
Posting Komentar (Atom)








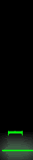

0 komentar:
Posting Komentar