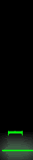Ibu Widarmi dan Yulianus Kuayo dari Depdiknas
oleh Dr. Alva Edy Tamtowi (Dosen Universitas Gadjah Mada)
dalam acara penutupan
“Bersatu Untuk Maju Selangkah, Menuju Perubahan”
Hari pertama
Acara pelantikan dan seminar yang digelar oleh Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai Se-Jawa dan Bali tanggal 30-31 Januari 2009 di CD Bethesda Yogyakarta adalah lanjutan dari pemilihan BPH yang pernah dilakukan pada tanggal 8-9 Agustus 2008. Dengan adanya pelantikan tersebut, Badan Pengurus Harian Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai resmi (sah) sebagaimana seperti paguyuban lainnya, demi melakukan kegiatan-kegiatan untuk mendukung orang pribadi dalam mengembangkan kemampuan yang dimilikinya di luar sekolah dan kampus. Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai Se-Jawa dan Bali yang belakangan dikenal dengan sebutan IPMADO berdiri setelah terjadinya pemekaran kabupaten baru (Dogiyai) yang dimekarkan dari kabupaten induk Nabire, beberapa waktu yang lalu.
Dalam acara pelantikan tersebut, awalnya dibuka dengan ibadah singkat yang dibawakan oleh Pdt. Benny Dimara, MA., sekitar pukul 08.30 dimana dalam khotbahnya ia (Pdt. Benny, red) meminta agar menjaga persatuan diantara semua invidu dalam tubuh IPAMDO yang ada di Jawa dan Bali, agar terjadi suatu perubahan pada diri sesorang dan Dogiyai ke depan. Ikatan Dogiyai merupakan Ikatan yang baru dilahirkan atau didirikan, sehingga diharapkan dalam program kerjanya berlandaskan Tuhan agar selalu dinaungi dalam semua kegiatan IPMADO Se-Jawa dan Bali ke depan lanjutnya. Pelantikan IPMADO yang dilantik oleh Pdt. Benny Dimara, MA., ini dalam pelantikannya menyebutkan nama Tuhan, sambil mengangkat Alkitab di atas kepala BPH terpilih.
Pelantikan yang dihadiri oleh anggota IPMADO Se-Jawa dan Bali serta utusan dari beberapa paguyuban yang ada di Yogyakarta ini berjalan lancar. walau anggota yang hadir pada saat itu kurang dari anggota seluruhnya. Pelantikan tersebut melibatkan masing-masing kordinator wilayah yang terbagi dalam 4 (empat) yakni Korwil I (Yogyakarta dan Solo), Korwil II Jatim (Surabaya, Malang dan Bali), Korwil III Jateng (Semarang, Salatiga), Korwil IV Jabar (Bandung dan Jabodetabek). Dengan adanya 4 kordinator wilayah, maka IPMADO pusat hanya sebagai pengontrol dan pembuat keputusan serta menjadi jembatan antara pelajar dan mahasiswa yang ada di Jawa dan Bali dengan pemerintah daerah Dogiyai. Program kerja IPMADO jangka pendek dan menengah dalam rangka mengembangkan Sumber Daya Manusia jangka pendek dijalankan oleh keempat kordinator wilayah tersebut, dan IPMADO pusat mengeluarkan surat keputusan untuk melakukan kegiatan yang melibatkan seluruh pelajar dan mahasiswa dari Jawa dan Bali. Sedangkan program kerja jangka panjang dilakukan oleh IPMADO pusat dan dibantu oleh setiap korwil yang ada.
Hari Kedua
Pada hari yang ke dua adalah seminar tentang Pendidikan Luar Sekolah yang dibawakan oleh Yulianus Kuayo, SH. dan Ibu Widarmi Dipawirya Wijana, MM. Dalam seminar tersebut dibahas tentang betapa minimnya Sumber Daya Manusia di Dogiyai, sehingga untuk meningkatkan SDM mahasiswa dituntut untuk memiliki keahlian tertentu sesuai kebutuhan masyarakat Dogiyai. Keahlian yang dimiliki mahasiswa adalah dalam rangka membantu pemerintah daerah manuju masyarakat Dogiyai yang sejahtera. Pada sesi yang kedua adalah dengan topik Spritual Orang Kristen Papua oleh Medex Pakage dari Yayasan Biterbusih (Bina Teruna Cenderawasih) dalam pemaparan seminarnya tentang kebiasaan orang Kristen Papua dalam kehidupan sehari-hari, hambatan dan tantangan orang Papua dalam membangun gereja saat ini, serta kehidupan orang Kristen Papua di Jawa. Oleh sebab itu empat pilar yang perlu diperhatikan dan dilakukan oleh pelajar dan Mahasiswa di Jawa saat ini yakni: a). membina dan membangun spiritualitas, b). membina dan membangun intelektualitas, c). membina dan membangun emosional, d). ora et labora (berdoa sambil bekerja). Semua tujuan, harapan, cita-cita, rencana dan niat baik tanpa berdoa dan beribadah akan sia-sia bahkan tidak akan terwujud. Inilah tugas dan kewajiban kita semua yaitu; berdoa, berdoa, dan berdoa, belajar, belajar dan belajar untuk membangun Dogiyai pada khususnya dan Papua pada umumnya, katanya sambil sambil menutup seminarnya. Bantuan dari Binterbusih memberikan modal berupa uang kepada panitia penyelenggara sebesar 300.000,- untuk menjawab proposal yang diajukan panitia kepada Binterbusih.
Sesi ketiga dengan topik Kreativitas Mahasiswa yang di Dr. Alva Edy Tontowi, dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta. Pada awal seminarnya Alva mengatakan bahwa alam kita telah menyediakan semuanya, tinggal bagaimana manusia itu menggunakannya. Hasil kreativitas manusia direalkan menjadi inovasi. Dan hasil inovasi ini merupakan salah satu cara untuk mengurangi penganguran di kampung dengan menggarap tenaga kerja dari kampung. Orang kreatif pada akhirnya disebut creator, dan motivasi untuk menciptakan inovasi ada dalam diri seseorang dan juga dari luar kata Dr. Alva Edy tantowi.
Hari Ketiga
Pada hari ketiga adalah hari penutupan dari rangkaian acara yang telah dilewati bersama. Bakar batu (ekina gapi) itulah tradisi bagi suku Mee yang mendiami pegunungan tengah Papua yang mana jika melakukan suatu kegiatan yang melibatkan banyak orang ditutup dengan pertumpahan darah babi. Bakar batu tersebut berlangsung di belakang Kampus Akademi Pariwisata Yogyakarta. Alam terbuka bersama udara segar di bawah pohon menambah kenyamanan pada saat menyantap gapita ekina.
Akhir kata seluruh Pelajar dan Mahasiswa Dogiyai yang ada di Jawa dan Bali menyampaikan banyak terimakasih kepada semua fihak yang membantu kami dalam menyukseskan acara ini. Suksesnya acara ini adalah karena atas keterlibatan kita semua. (Egeidaby).